Biografi
Ir. Soekarno
Soekarno
dilahirkan dengan nama Kusno Sosrodihardjo. Ayahnya bernama Raden Soekemi
Sosrodihardjo, seorang guru di Surabaya, Jawa. Ibunya bernama Ida Ayu Nyoman
Rai berasal dari Buleleng, Bali Ketika kecil Soekarno tinggal bersama kakeknya
di Tulungagung, Jawa Timur. Pada usia 14 tahun, seorang kawan bapaknya yang
bernama Oemar Said Tjokroaminoto mengajak Soekarno tinggal di Surabaya dan
disekolahkan ke Hoogere Burger School (H.B.S.) di sana sambil mengaji di tempat
Tjokroaminoto.
Di Surabaya, Soekarno banyak bertemu
dengan para pemimpin Sarekat Islam, organisasi yang dipimpin Tjokroaminoto saat
itu. Soekarno kemudian bergabung dengan organisasi Jong Java (Pemuda Jawa).Tamat H.B.S. tahun 1920, Soekarno melanjutkan ke Technische Hoge School (sekarang ITB) di Bandung, dan tamat pada tahun 1925. Saat di Bandung, Soekarno berinteraksi dengan Tjipto Mangunkusumo dan Dr. Douwes Dekker, yang saat itu merupakan pemimpin organisasi National Indische Partij. Pada tahun 1926, Soekarno mendirikan Algemene Studie Club di Bandung. Organisasi ini menjadi cikal bakal Partai Nasional Indonesia yang didirikan pada tahun 1927. Aktivitas Soekarno di PNI menyebabkannya ditangkap Belanda pada bulan Desember 1929, dan memunculkan pledoinya yang fenomenal: Indonesia Menggugat, hingga dibebaskan kembali pada tanggal 31 Desember 1931. Pada bulan Juli 1932, Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia (Partindo), yang merupakan pecahan dari PNI. Soekarno kembali ditangkap pada bulan Agustus 1933, dan diasingkan ke Flores. Di sini, Soekarno hampir dilupakan oleh tokoh-tokoh nasional.
Namun semangatnya tetap membara seperti tersirat dalam setiap suratnya kepada seorang Guru Persatuan Islam bernama Ahmad Hassan. Pada awal masa penjajahan Jepang (1942-1945), pemerintah Jepang sempat tidak memperhatikan tokoh-tokoh pergerakan Indonesia terutama untuk "mengamankan" keberadaannya di Indonesia. Ini terlihat pada Gerakan 3A dengan tokohnya Shimizu dan Mr. Syamsuddin yang kurang begitu populer. Namun akhirnya, pemerintahan pendudukan Jepang memperhatikan dan sekaligus memanfaatkan tokoh tokoh Indonesia seperti Soekarno, Mohammad Hatta dan lain-lain dalam setiap organisasi- organisasi dan lembaga lembaga untuk menarik hati penduduk Indonesia. Disebutkan dalam berbagai organisasi seperti Jawa Hokokai, Pusat Tenaga Rakyat (Putera),
Biografi Muh. Hatta
Masa Pembuangan
Pada bulan Januari 1935, Hatta dan kawan-kawannya tiba di Tanah Merah, Boven Digoel (Papua). Kepala pemerintahan di sana, Kapten van Langen, menawarkan dua pilihan: bekerja untuk pemerintahan kolonial dengan upah 40 sen sehari dengan harapan nanti akan dikirim pulang ke daerah asal, atau menjadi buangan dengan menerima bahan makanan in natura, dengan tiada harapan akan dipulangkan ke daerah asal. Hatta menjawab, bila dia mau bekerja untuk pemerintah kolonial waktu dia masih di Jakarta, pasti telah menjadi orang besar dengan gaji besar pula. Maka tak perlulah dia ke Tanah Merah untuk menjadi kuli dengan gaji 40 sen sehari.
Dalam pembuangan, Hatta secara teratur menulis artikel-artikel untuk surat kabar Pemandangan. Honorariumnya cukup untuk biaya hidup di Tanah Merah dan dia dapat pula membantu kawan-kawannya. Rumahnya di Digoel dipenuhi oleh buku-bukunya yang khusus dibawa dari Jakarta sebanyak 16 peti. Dengan demikian, Hatta mempunyai cukup banyak bahan untuk memberikan pelajaran kepada kawan-kawannya di pembuangan mengenai ilmu ekonomi, sejarah, dan filsafat. Kumpulan bahan-bahan pelajaran itu di kemudian hari dibukukan dengan judul-judul antara lain, "Pengantar ke Jalan llmu dan Pengetahuan" dan "Alam Pikiran Yunani." (empat jilid).
Pada bulan Desember 1935, Kapten Wiarda, pengganti van Langen, memberitahukan bahwa tempat pembuangan Hatta dan Sjahrir dipindah ke Bandaneira. Pada Januari 1936 keduanya berangkat ke Bandaneira. Mereka bertemu Dr. Tjipto Mangunkusumo dan Mr. Iwa Kusumasumantri. Di Bandaneira, Hatta dan Sjahrir dapat bergaul bebas dengan penduduk setempat dan memberi pelajaran kepada anak-anak setempat dalam bidang sejarah, tatabuku, politik, dan lain-Iain.
Kembali Ke Jawa: Masa Pendudukan Jepang
Pada tanggal 3 Pebruari 1942, Hatta dan Sjahrir dibawa ke Sukabumi. Pada tanggal 9 Maret 1942, Pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada Jepang, dan pada tanggal 22 Maret 1942 Hatta dan Sjahrir dibawa ke Jakarta.
Pada masa pendudukan Jepang, Hatta diminta untuk bekerja sama sebagai penasehat. Hatta mengatakan tentang cita-cita bangsa Indonesia untuk merdeka, dan dia bertanya, apakah Jepang akan menjajah Indonesia? Kepala pemerintahan harian sementara, Mayor Jenderal Harada. menjawab bahwa Jepang tidak akan menjajah. Namun Hatta mengetahui, bahwa Kemerdekaan Indonesia dalam pemahaman Jepang berbeda dengan pengertiannya sendiri. Pengakuan Indonesia Merdeka oleh Jepang perlu bagi Hatta sebagai senjata terhadap Sekutu kelak. Bila Jepang yang fasis itu mau mengakui, apakah sekutu yang demokratis tidak akan mau? Karena itulah maka Jepang selalu didesaknya untuk memberi pengakuan tersebut, yang baru diperoleh pada bulan September 1944.
Selama masa pendudukan Jepang, Hatta tidak banyak bicara. Namun pidato yang diucapkan di Lapangan Ikada (sekarang Lapangan Merdeka) pada tanggaI 8 Desember 1942 menggemparkan banyak kalangan. Ia mengatakan, "Indonesia terlepas dari penjajahan imperialisme Belanda. Dan oleh karena itu ia tak ingin menjadi jajahan kembali. Tua dan muda merasakan ini setajam-tajamnya. Bagi pemuda Indonesia, ia Iebih suka melihat Indonesia tenggelam ke dalam lautan daripada mempunyainya sebagai jajahan orang kembali.
Pada bulan Januari 1935, Hatta dan kawan-kawannya tiba di Tanah Merah, Boven Digoel (Papua). Kepala pemerintahan di sana, Kapten van Langen, menawarkan dua pilihan: bekerja untuk pemerintahan kolonial dengan upah 40 sen sehari dengan harapan nanti akan dikirim pulang ke daerah asal, atau menjadi buangan dengan menerima bahan makanan in natura, dengan tiada harapan akan dipulangkan ke daerah asal. Hatta menjawab, bila dia mau bekerja untuk pemerintah kolonial waktu dia masih di Jakarta, pasti telah menjadi orang besar dengan gaji besar pula. Maka tak perlulah dia ke Tanah Merah untuk menjadi kuli dengan gaji 40 sen sehari.
Dalam pembuangan, Hatta secara teratur menulis artikel-artikel untuk surat kabar Pemandangan. Honorariumnya cukup untuk biaya hidup di Tanah Merah dan dia dapat pula membantu kawan-kawannya. Rumahnya di Digoel dipenuhi oleh buku-bukunya yang khusus dibawa dari Jakarta sebanyak 16 peti. Dengan demikian, Hatta mempunyai cukup banyak bahan untuk memberikan pelajaran kepada kawan-kawannya di pembuangan mengenai ilmu ekonomi, sejarah, dan filsafat. Kumpulan bahan-bahan pelajaran itu di kemudian hari dibukukan dengan judul-judul antara lain, "Pengantar ke Jalan llmu dan Pengetahuan" dan "Alam Pikiran Yunani." (empat jilid).
Pada bulan Desember 1935, Kapten Wiarda, pengganti van Langen, memberitahukan bahwa tempat pembuangan Hatta dan Sjahrir dipindah ke Bandaneira. Pada Januari 1936 keduanya berangkat ke Bandaneira. Mereka bertemu Dr. Tjipto Mangunkusumo dan Mr. Iwa Kusumasumantri. Di Bandaneira, Hatta dan Sjahrir dapat bergaul bebas dengan penduduk setempat dan memberi pelajaran kepada anak-anak setempat dalam bidang sejarah, tatabuku, politik, dan lain-Iain.
Kembali Ke Jawa: Masa Pendudukan Jepang
Pada tanggal 3 Pebruari 1942, Hatta dan Sjahrir dibawa ke Sukabumi. Pada tanggal 9 Maret 1942, Pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada Jepang, dan pada tanggal 22 Maret 1942 Hatta dan Sjahrir dibawa ke Jakarta.
Pada masa pendudukan Jepang, Hatta diminta untuk bekerja sama sebagai penasehat. Hatta mengatakan tentang cita-cita bangsa Indonesia untuk merdeka, dan dia bertanya, apakah Jepang akan menjajah Indonesia? Kepala pemerintahan harian sementara, Mayor Jenderal Harada. menjawab bahwa Jepang tidak akan menjajah. Namun Hatta mengetahui, bahwa Kemerdekaan Indonesia dalam pemahaman Jepang berbeda dengan pengertiannya sendiri. Pengakuan Indonesia Merdeka oleh Jepang perlu bagi Hatta sebagai senjata terhadap Sekutu kelak. Bila Jepang yang fasis itu mau mengakui, apakah sekutu yang demokratis tidak akan mau? Karena itulah maka Jepang selalu didesaknya untuk memberi pengakuan tersebut, yang baru diperoleh pada bulan September 1944.
Selama masa pendudukan Jepang, Hatta tidak banyak bicara. Namun pidato yang diucapkan di Lapangan Ikada (sekarang Lapangan Merdeka) pada tanggaI 8 Desember 1942 menggemparkan banyak kalangan. Ia mengatakan, "Indonesia terlepas dari penjajahan imperialisme Belanda. Dan oleh karena itu ia tak ingin menjadi jajahan kembali. Tua dan muda merasakan ini setajam-tajamnya. Bagi pemuda Indonesia, ia Iebih suka melihat Indonesia tenggelam ke dalam lautan daripada mempunyainya sebagai jajahan orang kembali.
Boigrafi
Jend. Sudirman
Nama
Lengkap : Raden Soedirman
Nama
Lain: Jendral Sudirman
Tempat
Lahir : Desa Bodas Karangjati | Purbalingga | Jawa
Tengah
Tanggal
Lahir : Senin | 24 Januari 1916
Kebangsaan
: Indonesia
Meninggal : Magelang | 29 Januari 1950
Dimakamkan : Taman Makam Pahlawan Semaki
Meninggal : Magelang | 29 Januari 1950
Dimakamkan : Taman Makam Pahlawan Semaki
Agama
: Islam
Jendral Sudirman
merupakan sosok pahlawan nasional. Beliau lahir pada tanggal 24 Januari pada
tahun 1916 di kota Purbalingga, tepatnya di Dukuh Rembang. Beliau lahir dari
sosok ayah yang bernama Karsid Kartowirodji, danseorang ibu yang bernama Siyem.
Ayah dari Sudirman ini merupakan seorang pekerja di Pabrik Gula Kalibagor,
Banyumas, dan ibunya merupakan keturunan Wedana Rembang. Jendral Sudirman
dirawat oleh Raden Tjokrosoenarjo dan istrinya yang bernama Toeridowati.
Jenderal Sudirman mengenyam pendidikan keguruan yang bernama HIK. Beliau belajar di tempat tersebut selama satu tahun. Hal ini beliau lakukan setelah selesai melaksanakan belajarnya di Wirotomo. Sudirman diangkat menjadi seorang Jendral pada umurnya yang menginjak 31 tahun. Beliau merupakan orang termuda dan sekaligus pertama di Indonesia. Sejak kecil, beliau merupakan seorang anak yang pandai dan juga sangat menyukai organisasi. Dimulai dari organisasi yang terdapat di sekolahnya dahulu, beliau sudah menunjukkan criteria pemimpin yang disukai di masyarakat. Keaktifan beliau pada pramuka hizbul watan menjadikan beliau seorang guru sekolah dasar Muhammadiyah di kabupaten Cilacap. Lalu beliau berlanjut menjadi seorang kepala sekolah.
Jendral Sudirman juga pernah masuk ke dalam belajar militer di PETA (Pembela Tanah Air) yang berada di kota Bogor. Pendidikan di PETA dilakukan oleh tentara Jepang pada sat itu. Ketika sudah menyelesaikan pendidikannya di PETA, kemudian beliau menjadi seorang Komandan Batalyon yang berada di Kroya, Jawa Tengah. Kepemimpinan beliau tidak berhenti sampai situ, beliau juga menjadi seorang panglima di kota Banyumas.
beliau pernah menjadi seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat di kota Banyumas. Jenderal Sudirman terpilih menjadi seorang panglima angkatan perang pada tanggal 12 November 1945. Beberapa perang melawan penjajah telah beliau pimpin seperti perang melawan tentara Inggris di Ambarawa, memimpin pasukannya untuk membela Yogyakarta dari serangan Belanda II. Pada tahun 1950 beliau ini wafat. Beliau wafat karena terjangkit penyakit tuberculosis. Panglima besar Sudirman ini dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara di Semaki, Yogyakarta.
Jenderal Sudirman mengenyam pendidikan keguruan yang bernama HIK. Beliau belajar di tempat tersebut selama satu tahun. Hal ini beliau lakukan setelah selesai melaksanakan belajarnya di Wirotomo. Sudirman diangkat menjadi seorang Jendral pada umurnya yang menginjak 31 tahun. Beliau merupakan orang termuda dan sekaligus pertama di Indonesia. Sejak kecil, beliau merupakan seorang anak yang pandai dan juga sangat menyukai organisasi. Dimulai dari organisasi yang terdapat di sekolahnya dahulu, beliau sudah menunjukkan criteria pemimpin yang disukai di masyarakat. Keaktifan beliau pada pramuka hizbul watan menjadikan beliau seorang guru sekolah dasar Muhammadiyah di kabupaten Cilacap. Lalu beliau berlanjut menjadi seorang kepala sekolah.
Jendral Sudirman juga pernah masuk ke dalam belajar militer di PETA (Pembela Tanah Air) yang berada di kota Bogor. Pendidikan di PETA dilakukan oleh tentara Jepang pada sat itu. Ketika sudah menyelesaikan pendidikannya di PETA, kemudian beliau menjadi seorang Komandan Batalyon yang berada di Kroya, Jawa Tengah. Kepemimpinan beliau tidak berhenti sampai situ, beliau juga menjadi seorang panglima di kota Banyumas.
beliau pernah menjadi seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat di kota Banyumas. Jenderal Sudirman terpilih menjadi seorang panglima angkatan perang pada tanggal 12 November 1945. Beberapa perang melawan penjajah telah beliau pimpin seperti perang melawan tentara Inggris di Ambarawa, memimpin pasukannya untuk membela Yogyakarta dari serangan Belanda II. Pada tahun 1950 beliau ini wafat. Beliau wafat karena terjangkit penyakit tuberculosis. Panglima besar Sudirman ini dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara di Semaki, Yogyakarta.
Nama dan Biografi Singkat Pahlawan Revolusi
1.Jenderal Ahmad Yani
Jenderal TNI
Anumerta Yani lahir di Jawa Tengah, 19
Juni 1922 meninggal di Lubang Buaya, 1 Oktober 1965 pada umur 43 tahun.
Adalah komandan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan dibunuh oleh
anggota Gerakan 30 September. Ahmad
lahir di Jenar Purworejo, Jawa Tengah pada tanggal 19 Juni 1922 di
keluarga Wongsoredjo, keluarga yang bekerja di sebuah pabrik gula yang
dijalankan oleh pemilik Belanda. Pada tahun 1927, Yani pindah dengan
keluarganya ke Batavia, di mana ayahnya kini bekerja untuk General Belanda. Di
Batavia, Yani bekerja jalan melalui pendidikan dasar dan menengah. Pada tahun
1940, Yani meninggalkan sekolah tinggi untuk menjalani wajib militer di tentara
Hindia Belanda pemerintah kolonial. Ia belajar topografi militer di Malang,
Jawa Timur, pendidikan ini terganggu oleh kedatangan pasukan Jepang pada tahun
1942. Pada saat yang sama, Yani dan keluarganya pindah kembali ke Jawa
Tengah.Pada tahun 1943, ia bergabung dengan tentara yang disponsori Jepang Peta
(Pembela Tanah Air), dan menjalani pelatihan lebih lanjut di Magelang. Setelah
menyelesaikan pelatihan ini, Yani meminta untuk dilatih sebagai komandan
peleton Peta dan dipindahkan ke Bogor, Jawa Barat untuk menerima pelatihan.
Setelah selesai, ia dikirim kembali ke Magelang sebagai instruktur.
2.Letnan Jenderal R. Suprapto
3.Letnan Jenderal Haryono
4 .Letnan Jenderal Siswondo Parman
Letnan
Jenderal TNI Anumerta Siswondo Parman lahir di Wonosobo Jawa Tengah, 4 Agustus
1918. Meninggal di Lubang Buaya Jakarta, 1 Oktober 1965 pada umur 47 tahun.
Siswondo Parman atau lebih dikenal dengan nama S. Parman adalah salah satu pahlawan
revolusi Indonesia dan tokoh militer Indonesia. Ia meninggal dibunuh pada
persitiwa Gerakan 30 September dan mendapatkan gelar Letnan Jenderal Anumerta.
Ia dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta.Parman merupakan perwira intelijen,
sehingga banyak tahu tentang kegiatan PKI. Dia termasuk salah satu di antara
para perwira yang menolak rencana PKI untuk membentuk Angkatan Kelima yang
terdiri dari buruh dan tani. Penolakan serta posisinya sebagai pejabat
intelijen yang tahu banyak tentang PKI, membuatnya menjadi korban penculikan
oleh Resimen Tjakrabirawa yang dipimpin Serma Satar. Penculikannya diduga
diatur oleh kakak kandungnya sendiri, yaitu Ir. Sakirman yang merupakan
petinggi di Politbiro CC PKI kala itu.
5.Mayor Jenderal Pandjaitan
Brigadir
Jenderal TNI Anumerta Donald Isaac Panjaitan lahir di Sumatera Utara, 19 Juni
1925. Meninggal di Lubang Buaya, Jakarta, 1 Oktober 1965 pada umur 40 tahun)
adalah salah satu pahlawan revolusi Indonesia. Ia dimakamkan di Taman Makam
Pahlawan Kalibata, Jakarta. Pendidikan formal diawali dari Sekolah Dasar,
kemudian masuk Sekolah Menengah Pertama, dan terakhir di Sekolah Menengah Atas.
Ketika ia tamat Sekolah Menengah Atas, Indonesia sedang dalam pendudukan
Jepang. Sehingga ketika masuk menjadi anggota militer ia harus mengikuti
latihan Gyugun. Selesai latihan, ia ditugaskan sebagai anggota Gyugun di
Pekanbaru, Riau hingga Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya.Ketika
Indonesia sudah meraih kemerdekaan, ia bersama para pemuda lainnya membentuk
Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang kemudian menjadi TNI. Di TKR, ia pertama
kali ditugaskan menjadi komandan batalyon, kemudian menjadi Komandan Pendidikan
Divisi IX/Banteng di Bukittinggi pada tahun 1948. Seterusnya menjadi Kepala
Staf Umum IV (Supplay) Komandemen Tentara Sumatera. Dan ketika Pasukan Belanda
melakukan Agresi Militernya yang Ke II, ia diangkat menjadi Pimpinan Perbekalan
Perjuangan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI).Seiring dengan
berakhirnya Agresi Militer Belanda ke II, Indonesia pun memperoleh pengakuan
kedaulatan. Panjaitan sendiri kemudian diangkat menjadi Kepala Staf Operasi
Tentara dan Teritorium (T&T) I Bukit Barisan di Medan. Selanjutnya
dipindahkan lagi ke Palembang menjadi Kepala Staf T & T
II/Sriwijaya.Setelah mengikuti kursus Militer Atase (Milat) tahun 1956, ia
ditugaskan sebagai Atase Militer RI di Bonn, Jerman Barat. Ketika masa tugasnya
telah berakhir sebagai Atase Militer, ia pun pulang ke Indonesia. Namun tidak
lama setelah itu yakni pada tahun 1962, perwira yang pernah menimba ilmu pada
Associated Command and General Staff College, Amerika Serikat ini, ditunjuk
menjadi Asisten IV Menteri/Panglima Angkatan Darat (Men/Pangad). Jabatan inilah
terakhir yang diembannya saat peristiwa G 30/S PKI terjadi. Ketika menjabat
Asisten IV Men/Pangad, ia mencatat prestasi tersendiri atas keberhasilannya
membongkar rahasia pengiriman senjata dari Republik Rakyat Cina (RRC) untuk
PKI. Dari situ diketahui bahwa senjata-senjata tersebut dimasukkan ke dalam
peti-peti bahan bangunan yang akan dipakai dalam pembangunan gedung Conefo
(Conference of the New Emerging Forces). Senjata-senjata itu diperlukan PKI
yang sedang giatnya mengadakan persiapan melancarkan pemberontakan.
6.Mayor Jenderal Sutoyo Siswomiharjo
Mayor
Jendral TNI Anumerta Sutoyo Siswomiharjo lahir di Jawa Tengah, 28 Agustus 1922.
Meninggal di Lubang Buaya Jakarta, 1 Oktober 1965 pada umur 43 tahun. adalah
seorang perwira tinggi TNI-AD yang diculik dan kemudian dibunuh dalam peristiwa
Gerakan 30 September di Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia
pada tahun 1945, Sutoyo bergabung ke dalam bagian Polisi Tentara Keamanan
Rakyat (TKR), cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. Hal ini kemudian menjadi
Polisi Militer Indonesia. Pada Juni 1946, ia diangkat menjadi ajudan Kolonel
Gatot Soebroto, komandan Polisi Militer. Ia terus mengalami kenaikan pangkat di
dalam Polisi Militer, dan pada tahun 1954 ia menjadi kepala staf di Markas
Besar Polisi Militer. Dia memegang posisi ini selama dua tahun sebelum diangkat
menjadi asisten atase militer di kedutaan besar Indonesia di London. Setelah
pelatihan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat di Bandung dari tahun 1959
hingga 1960, ia diangkat menjadi Inspektur Kehakiman Angkatan Darat, kemudian
karena pengalaman hukumnya, pada tahun 1961 ia menjadi inspektur
kehakiman/jaksa militer utama. Pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965, anggota
Gerakan 30 September yang dipimpin oleh Sersan Mayor Surono masuk ke dalam
rumah Sutoyo di Jalan Sumenep, Menteng, Jakarta Pusat. Mereka masuk melalui
garasi di samping rumah. Mereka memaksa pembantu untuk menyerahkan kunci, masuk
ke rumah itu dan mengatakan bahwa Sutoyo telah dipanggil oleh Presiden
Soekarno. Mereka kemudian membawanya ke markas mereka di Lubang Buaya. Di sana,
dia dibunuh dan tubuhnya dilemparkan ke dalam sumur yang tak terpakai. Seperti
rekan-rekan lainnya yang dibunuh, mayatnya ditemukan pada 4 Oktober dan dia
dimakamkan pada hari berikutnya. Dia secara anumerta dipromosikan menjadi Mayor
Jenderal dan menjadi Pahlawan Revolusi.
7.Kapten Pierre Tendean
Kapten CZI Anumerta Pierre Andreas Tendean lahir 21 Februari 1939 –
meninggal 1 Oktober 1965 pada umur 26 tahun. adalah seorang perwira militer
Indonesia yang menjadi salah satu korban peristiwa Gerakan 30 September pada
tahun 1965. Mengawali karier militer dengan menjadi intelijen dan kemudian
ditunjuk sebagai ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution dengan pangkat letnan
satu, ia dipromosikan menjadi kapten anumerta setelah kematiannya. Tendean
dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dan bersama enam perwira korban
G30S lainnya, ia ditetapkan sebagai Pahlawan Revolusi Indonesia pada tanggal 5
Oktober 1965. Pierre Andreas Tendean terlahir dari pasangan Dr. A.L Tendean,
seorang dokter yang berdarah Minahasa, dan Cornet M.E, seorang wanita Indo yang
berdarah Perancis, pada tanggal 21 Februari 1939 di Batavia (kini Jakarta),
Hindia Belanda. Pierre adalah anak kedua dari tiga bersaudara; kakak dan
adiknya masing-masing bernama Mitze Farre dan Rooswidiati. Tendean mengenyam
sekolah dasar di Magelang, lalu melanjutkan SMP dan SMA di Semarang tempat
ayahnya bertugas. Sejak kecil, ia sangat ingin menjadi tentara dan masuk
akademi militer, namun orang tuanya ingin ia menjadi seorang dokter seperti
ayahnya atau seorang insinyur. Karena tekadnya yang kuat, ia pun berhasil
bergabung dengan Akademi Teknik Angkatan Darat (ATEKAD) di Bandung pada tahun
1958.Pada pagi tanggal 1 Oktober 1965, pasukan Gerakan 30 September (G30S)
mendatangi rumah Nasution dengan tujuan untuk menculiknya. Tendean yang sedang
tidur di ruang belakang rumah Jenderal Nasution terbangun karena suara tembakan
dan ribut-ribut dan segera berlari ke bagian depan rumah. Ia ditangkap oleh
gerombolan G30S yang mengira dirinya sebagai Nasution karena kondisi rumah yang
gelap. Nasution sendiri berhasil melarikan diri dengan melompati pagar. Tendean
lalu di bawa ke sebuah rumah di daerah Lubang Buaya bersama enam perwira tinggi
lainnya. Ia ditembak mati dan mayatnya dibuang ke sebuah sumur tua bersama enam
jasad perwira lainnya.
Konfrensi
Meja Bundar
Setelah
bangsa Indonesia berhasil menyelesaikan masalahnya sendiri dalam Konferensi
Inter-Indonesia maka bangsa Indonesia secara keseluruhan menghadapi Konferensi
Meja Bundar, Sementara itu pada hulan Agustus 1949, Presiden Soekamo sebagai
Panglima Tertinggi di satu pihak dan Wakil Tinggi Mahkota Belanda di lain pihak
memgumumkan perintah penghentian tembak-menembak. Perintah itu beriaku mulai
tanggal 11 Agustus 1949 untuk Jawa dan 15 Agustus 1949 untuk Sumatra. Pada
tanggal 11 Agustus 1949, dibentuk delegasi Republik Endonesia untuk menghadapi
Konferensi Meja Bundar.
Delegasi itu terdiri dari Drs. Hatta
(ketua), Nir. Moh. Roem, Prof Dr. Mr. Supomo, Dr. J. Leitnena„ Mr. Ali
Sastroamicijojo, Ir. Djuanda, Dr. Sukiman, Mr. Suyono Hadinoto, Dr. Sumitro
Djojohadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringgodigdo, Kolonel T.B. Simatupang dan Mr.
Muwardi. Delegasi BF0 dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Pada
tanggal 23 Agustus 1949 Konferensi Meja Bundar dimulai di Den Haag,
Belanda. Konferensi ini berlangsung hingga tanggal 2 November 1949 dengan hasil
sebagai berikut.
1. Belanda mengakui Republik Indonesia
Serikat (RIS) sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.
2. Status Karesidenan Irian Barat
diselesaikan dalam waktu setahun, sesudah pengakuan kedaulatan.
3. Akan dibentuk Uni Indonesia-Belanda
berdasarkan kerja sama sukarela dan sederajat.
4. Republik Indonesia Serikat
mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak-hak konsesi dan izin baru
untuk perusahaan-perusahaan Belanda.
5. Republik indonesia Serikat harus
membayar semua utang Belanda yang ada sejak tahun 1942.
Dengan
demikian, KNIP menerima KMB. Pada tanagal 15 Desember 1949 diadakan pemilihan
Presiden RIS dengan caIon tunggal Ir. Soekarno dan terpilih sebagai presiden.
Kemudian dilantik dan diambil sumpahnya pada tanggal 17 Desember 1949. Kabinet
RIS di bawah pimpinan Drs. Moh. Hatta. Drs. Moh. Hatta dilantik sebagai perdana
menteri oleh Presiden Soekarno pada tanggal 20 Desember 1949. Selanjutnya pada
tanggal 23 Desember 1949 delegasi RIS berangkat ke negeri Belanda untuk
menandatangani akta penyerahan kedaulatan. Pada tanggal 27 Desember 1949, baik
di Indonesia maupun di negeri Belanda dilaksanakan upacara penandatanganan akta
penyerahan kedaulatan.
Dampak Konferensi Meja Bundar
Penyerahan kedaulatan yang dilakukan di negeri Belanda
bertempat di ruang takhta Amsterdam, Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem
Drees, Menteri Seberang Lautan A.M.J.A. Sasseu, dan Drs. Moh. Hatta melakukan
penandatanganan akta penyerahan kedaulatan. Pada saat yang sama di Jakarta, Sri
Sultan Hamengku Buwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota Belanda, A.H.S. Lovink dalam
suatu upacara di Istana Merdeka menandatangani naskah penyerahan kedaulatan.
Dengan
penyerahan kedaulatan itu, secara formal Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia
dan mengakui kekuasaan negara Indonesia di seluruh bekas wilayah Hindia
Belanda, kecuali Irian Barat yang akan diserahkan setahun kemudian. Sebulan
kemudian, yaitu pada tanggal 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman, Panglima Besar
Angkatan Perang Republik Indonesia meninggal dunia pada usia yang cukup muda,
yaitu 34 tahun. Beliau adalah tokoh panutan bagi para anggota TNI.
Perundingan Hooge Veluwe
Perundingan
Hooge Veluwe merupakan lanjutan pembicaraan-pembicaraan yang didasarkan atas
persetujuan yang telah disepakati antara Sjahrir dan Van Mook. Kesepakatan itu
tertuang dalam usul tandingan pemerintahan Indonesia tanggal 27 Maret 1946.
Perundingan itu diadakan di kota Hooge Veluwe (Negeri Belanda) tanggal 14-21
April 1946.
Pemberangkatan para delegasi Indonesia tanggal 4 April
1946 dengan menggunakan pesawat terbang Maskapai Penerbangan Belanda KLM. Dari
Belanda, di samping Van Mook juga ikut serta Dr. Indenburg (Sekretaris
Kabinet), Sultan Hamid (Sultan Pontianak), dan Sario Santoso (Kolonel KNIL).
Dari pihak Republik Indonesia adalah Menteri Kehakiman
Mr. Suwandi, Menteri Dalam Negeri Dr. Sudarsono, dan Sekretaris Kabinet Mr.
A.G.Pringgodigdo. Dengan pesawat yang sama juga berangkat Sir Archibald
Clark Keer beserta stafnya.
Dalam
perundingan Hooge Veluwe ini pihak-pihak yang berunding seperti berikut :
1. Delegasi
Belanda terdiri dari: Perdana Menteri Prof. Ir. Dr. W. Schermerhorn, Menteri
Daerah-daerah Seberang Lautan Prof. Dr. J.H. Logemann, Menteri Luar Negeri Dr.
J.H. Van Roijen, Letnan Gubernur Jenderal Dr. H.J. Van Mook, Prof. Baron van
Asbeck, Sultan Hamid II, dan Letnan Kolonel Surio Santoso.
2. Delegasi
Republik Indonesia terdiri dari Menteri Kehakiman Mr. Suwandi, Menteri Dalam
Negeri Dr. Sudarsono, dan Sekretaris Kabinet Mr. A.G. Pringgodigdo.
3. Pihak
perantara Sir Archibald Clark Keer beserta stafnya.
Perundingan Hooge Veluwe ini gagal, karena delegasi
Belanda tidak berpijak pada kesepakatan tanggal 27 Maret 1946 yang telah
disetujui bersama oleh Sjahrir-Van Mook. Kepada delegasi Indonesia ditawarkan
''protokol'' bukan ''perjanjian''.
Alasannya, Belanda tidak mengakui Republik Indonesia.
Protokol yang ditawarkan isinya juga menyimpang dari kesepakatan 17 Maret 1946.
Protokol hanya mencantumkan suatu Federasi Persemakmuran Indonesia, pengakuan
Pemerintah Belanda atas de facto Republik Indonesia atas Jawa
(bukan Pulau Jawa dan Sumatera).
Kegagalan perundingan Hooge Veluwe ini lebih banyak
disebabkan oleh pihak Belanda yang tidak dengan sungguh-sungguh menyelesaikan
sengketanya dengan Indonesia. Yang menarik bahwa Belanda mampu membuat
perpecahan di antara orang Indonesia dengan ikut sertanya dua orang Indonesia
dalam delegasi Belanda.
Hal ini menunjukan bahwa Belanda mampu memainkan
politik adu dombanya sehingga ada utusan yang berasal dari Indonesia tetapi
memiliki komitmen bergabung dengan kepentingan Belanda. Dengan kegagalan
perundingan ini maka hubungan antara Belanda dengan Indonesia menjadi sangat
buruk.
Akan tetapi pada tanggal 2 Mei 1946 Van Mook kembali
membawa usul pemerintahnya yang terdiri dari tiga pokok pikiran yaitu :
1.
Pemerintah Belanda mengakui Republik Indonesia sebagai bagian dari
persemakmuran (gemeennebest) Indonesia yang berbentuk federasi
(serikat).
2.
Persemakmuran Indonesia Serikat di satu pihak dengan Nederland, Suriname, dan
Curacao di lain pihak akan merupakan bagian-bagian dari kerajaan Belanda.
3.
Pemerintah Belanda akan mengakui de facto kekuasaan RI atas Jawa,
Madura, dan Sumatera dikurangi dengan daerah-daerah yang diduduki oleh tentara
Inggris dan Belanda (Marwati Djoened Poesponegoro, 1984:127).
Usul yang
dilakukan oleh Belanda itu ternyata tidak diterima oleh Republik Indonesia
karena dianggap tidak ada hal yang baru di dalamnya. Pihak Republik Indonesia
justru mengajukan usul baru terhadap Belanda yang isinya:
1. Republik
Indonesia berkuasa de facto atas Jawa, Medura, Sumatera, ditambah dengan
daerah-daerah yang dikuasai oleh tentara Inggris dan Belanda.
2. Repubilik
Indonesia menolak ikatan kenegaraan (dalam hal ini gemeennebest, rijkverband,
koloni, trusteenship territory atau federasi ala Vietnam) dan
menghendaki penghentian pengiriman pasukan Belanda ke Indonesia, sedangkan
pemerintah Indonesia tidak akan menambah pasukannya.
3.
Pemerintah Indonesia menolak suatu periode peralihan (over-gangs-periode)
dibawah kedaulatan Belanda (Mawarti Djoened Poesponegoro, 1984:127).
Perjanjian
Renville
Atas usulan
KTN pada tanggal 8 Desember 1947 dilaksanakan perundingan antara Indonesia dan
Belanada di atas kapal renville yang sedang berlabuh di Jakarta. Delegasi
Indonesia terdiri atas perdana menteri Amir Syarifudin, Ali Sastroamijoyo, Dr.
Tjoa Sik Len, Moh. Roem, Haji Agus Salim, Narsun dan Ir. Juanda. Delegasi
Belanda terdiri dari Abdulkadir Widjojoatmojo, Jhr. Van Vredeburgh, Dr. Soumukil,
Pangran Kartanagara dan Zulkarnain. Ternyata wakil-wakil Belanda hampir semua
berasala dari bangsa Indonesia sendiri yang pro Belanda. Dengan demikian
Belanda tetap melakukan politik adu domba agar Indonesia mudah dikuasainya.
Setelah selesai perdebatan dari tanggal 8 Desember 1947 sampai dengan 17
Januari 1948 maka diperoleh hasil persetujuan damai yang disebut Perjanjian
Renville. Pokok-poko isi perjanjian Renville, antara lain sebagai berikut :
1. Belanda tetap berdaulat atas seluruh
wilayah Indonesia samapi kedaulatan Indonesia diserahkan kepada Republik
Indonesia Serikat yang segera terbentuk.
2. Republik Indonesia Serikat mempunyai
kedudukan yang sejajar dengan negara Belanda dalam uni Indonesia-Belanda.
3. Republik Indonesia akan menjadi
negara bagian dari RIS
4. Sebelum RIS terbentuk, Belanda dapat
menyerahkan sebagain kekuasaannya kepada pemerintahan federal sementara.
5. Pasukan republic Indonesia yang
berda di derah kantong haruns ditarik ke daerah Republik Indonesia. Daerah
kantong adalah daerah yang berada di belakang Garis Van Mook, yakni garis yang
menghubungkan dua derah terdepan yang diduduki Belanda.
Perjanjian Renville ditandatangani
kedua belah pihak pada tanggal 17 Januari 1948. adapun kerugian yang diderita
Indonesia dengan penandatanganan perjanjian Renville adalah sebagai berikut :
1. Indonesia terpaksa menyetujui
dibentuknya negara Indonesia Serikat melalaui masa peralihan.
2. Indonesia kehilangan sebagaian
daerah kekuasaannya karena grais Van Mook terpaksa harus diakui sebagai daerah
kekuasaan Belanda.
3. Pihak republik Indonesia harus
menarik seluruh pasukanya yang berda di derah kekuasaan Belanda dan
kantong-kantong gerilya masuk ke daerah republic Indonesia.
Penandatanganan naskah perjanjian
Renville menimbulkan akibat buruk bagi pemerinthan republik Indonesia, antra
lain sebagai berikut:
1. Wilayah Republik Indonesia menjadi
makin sempit dan dikururung oleh daerah-daerah kekuasaan belanda.
2. Timbulnya reaksi kekerasan
dikalangan para pemimpin republic Indonesia yang mengakibatkan jatuhnya cabinet
Amir Syarifuddin karena dianggap menjual negara kepada Belanda.
3. Perekonomian Indonesia diblokade
secara ketata oleh Belanda
4. Indonesia terpaksa harus menarik
mundur kesatuan-kesatuan militernya dari daerah-daerah gerilya untuk kemudian
hijrah ke wilayah Republik Indonesia yang berdekatan.
5. Dalam usaha memecah belah Negara
kesatuan republic Indonesia, Belanda membentuk negara-negara boneka, seperti;
negara Borneo Barat, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, dan Negara jawa
Timut. Negara boneka tersebut tergabung dalam BFO (Bijeenkomstvoor Federal
Overslag).
Perundingan ROEM ROYEN
Dewan Keamanan PBB pada tanggal 23 Maret
1949 memerintahkan UNCI untuk pelaksanaan membantu perundingan antara Republik
Indonesia dan Belanda. Dalam pelaksanaan tugas tersebut akhirnya berhasil
membawa Indonesia dan Belanda ke meja perundingan, delagasi Indonesia diketuai
Mr Moh Roem sedangkan Belanda oleh Br Van Royen.
Pada tanggal 17 April 1949 dimulailah perundingan pendahuluan
di Jakarta yang diketuai oleh Merle Cochran, wakil Amerika Serikat dalam UNCI.
Dalam perundingan selanjutnya Indonesia diperkuat Drs Moh Hatta dan Sri Sultan
Hamengkubuwono IX.
Setelah melalui perundingan yang berlarut-larut akhirnya pada
tanggal 7 Mei 1949 tercapat persetujuan yang kemudian dikenal dengan nama Roem royen statement
Isi persetujuan adalah sebagai berikut:
Isi persetujuan adalah sebagai berikut:
Delegasi Indonesia menyatakan kesediaan Pemerintah RI untuk:
1. Mengeluarkan perintah kepada pengikut Republik yang
bersenjata untuk menghentikan perang gerilya.
2. Bekerjasama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga
ketertiban dan keamanan.
3. Turut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag
dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sunguh dan lengkap
kepada negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat.
Pernyataan Belanda pada pokoknya berisi:
1. Menyetujui kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta.
2. Membebaskan semua tahanan politik dan menjamin penghentian gerakan militer.
3. Tidak akan mendirikan negara-negara yang ada di daerah Republik dan dikuasainya dan tidak akan meluaskan daerah dengan merugikan Republik.
4. Menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat.
5. Berusaha dengan sungguh-sungguh supaya KMB segera diadakan setelah pemerintah Republik kembali ke Yogyakarta.
1. Menyetujui kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta.
2. Membebaskan semua tahanan politik dan menjamin penghentian gerakan militer.
3. Tidak akan mendirikan negara-negara yang ada di daerah Republik dan dikuasainya dan tidak akan meluaskan daerah dengan merugikan Republik.
4. Menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat.
5. Berusaha dengan sungguh-sungguh supaya KMB segera diadakan setelah pemerintah Republik kembali ke Yogyakarta.
Hasil perundingan ini mendapat reaksi keras dari berbagai
pihak di Indonesia, terutama dari pihak TNI dan PDRI, ialah sebagai berikut:
Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia Jenderal Sudirman pada tanggal 1 Mei 1949 mengeluarkan amanat yang ditujukan kepada komandan-komandan kesatuan memperingatkan agar mereka tidak turut memikirkan perundingan, karena akibatnya hanya akan merugikan pertahanan dan perjuangan.
Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia Jenderal Sudirman pada tanggal 1 Mei 1949 mengeluarkan amanat yang ditujukan kepada komandan-komandan kesatuan memperingatkan agar mereka tidak turut memikirkan perundingan, karena akibatnya hanya akan merugikan pertahanan dan perjuangan.
Amanat Panglima Besar Sudirman itu kemudian disusul dengan
maklumat-maklumat Markas Besar Komando Djawa (MBKD) yang meyerukan agar tetap
waspada, walaupun ada perundingan-perundingan yang menghasilkan persetujuan.
Perkiraan TNI terhadap kemungkinan serangan dari pihak
Belanda tidak meleset. Pasukan-pasukan Belanda yang ditarik dari Yogyakarta
dipindahkan ke Surakarta. Dengan bertambahnya kekuatan Belanda di Surakarta dan
akibatnya Letnan Kolonel Slamet Riyadi yang memimpin TNI di Surakarta
memerintahkan penyerangan-penyerangan terhadap obyek-obyek vital di Solo. Di
tempat lain pun perlawalan gerilya tetap berjalan, tanpa terpengaruh oleh
perundingan apa pun hasilnya.
Penghentian tembak-menembak
Bersamaan dengan berlangsunya konfensi inter-indonesia pada tanggal 1 agustus 1949 di Jakarta diadakan perundingan resmi antara Wakil-wakil RI BFO dan Belanda di bawah pengawasan UNCI yang menghasilkan Persetujuan Penghentian Permusuhan. Presiden selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang RI melalui Radio Republik Indonesia di Yogya pada tanggal 3 Agustus 1949 mengumumkan perintah menghentikan tembak-menembak, hal serupa dilakukan pula oleh Jenderal Sudirman, Panglima Besar TNI. Pada hari yang sama, AHJ Lovink, Wakil Tinggi Mahkota Kerajaan Belanda sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang Belanda di Indonesia memerintahkan kepada serdadu-serdadunya untuk meletakkan senjata, yang berarti kedua belah pihak menghentikan permusuhan secara resmi yang pelaksanaannya diawasi oleh KTN dari PBB.
Bersamaan dengan berlangsunya konfensi inter-indonesia pada tanggal 1 agustus 1949 di Jakarta diadakan perundingan resmi antara Wakil-wakil RI BFO dan Belanda di bawah pengawasan UNCI yang menghasilkan Persetujuan Penghentian Permusuhan. Presiden selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang RI melalui Radio Republik Indonesia di Yogya pada tanggal 3 Agustus 1949 mengumumkan perintah menghentikan tembak-menembak, hal serupa dilakukan pula oleh Jenderal Sudirman, Panglima Besar TNI. Pada hari yang sama, AHJ Lovink, Wakil Tinggi Mahkota Kerajaan Belanda sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang Belanda di Indonesia memerintahkan kepada serdadu-serdadunya untuk meletakkan senjata, yang berarti kedua belah pihak menghentikan permusuhan secara resmi yang pelaksanaannya diawasi oleh KTN dari PBB.
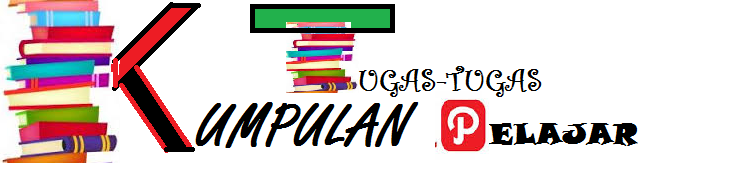


0 Komentar untuk "BIOGRAFI pejuang Indonesia, konfrensi pada zaman penjajahan"